Ditulis oleh Rianto dari acara webinar IDSCL, 27 April 2025.
Komunikasi sains belum dipelajari sebagai disiplin yang mapan dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Di berbagai negara, komunikasi sains telah berkembang sebagai mata kuliah atau bidang studi untuk menjembatani pemahaman sains kepada publik dan mendorong pembentukan pemahaman kolektif masyarakat terhadap isu-isu ilmiah dan kebijakan berbasis bukti. Pelbagai media komunikasi sains juga dipelajari agar mampu menjangkau audiens yang beragam.
Pertanyaan ini berulang kali masuk melalui pesan langsung ke akun Instagram IDSCL dan akun pribadi Ilham, menandakan meningkatnya minat namun sekaligus kebingungan publik akademik terhadap jalur formal maupun informal dalam bidang ini.
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, IDSCL menginisiasi diskusi terbuka melalui Zoom Meeting pada 27 April 2024 dengan menghadirkan dua narasumber yang memiliki pengalaman belajar komunikasi sains secara formal di luar negeri: Gusti Ayu Ismayanti dan Muhammad Galih Widiyanto.
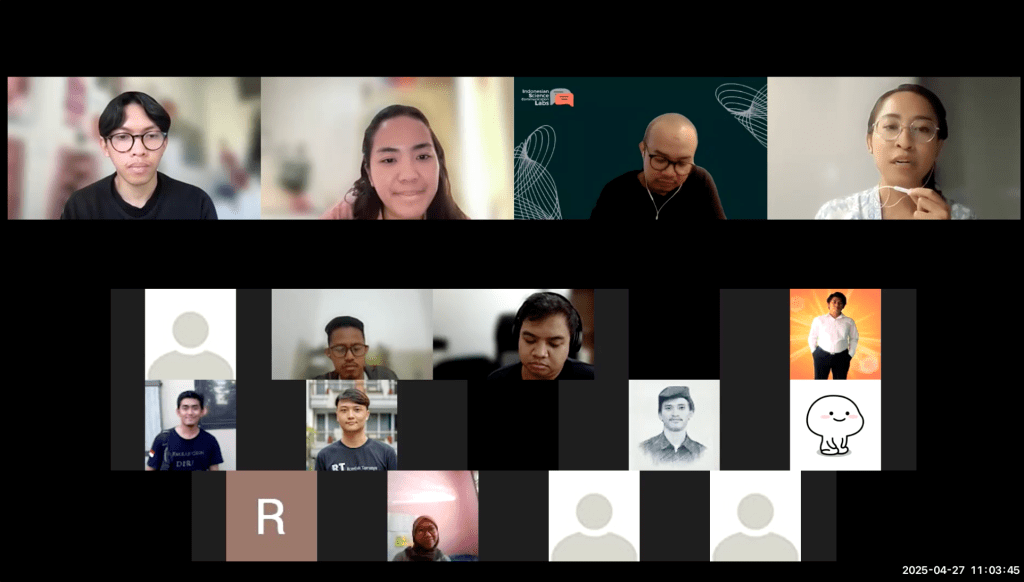
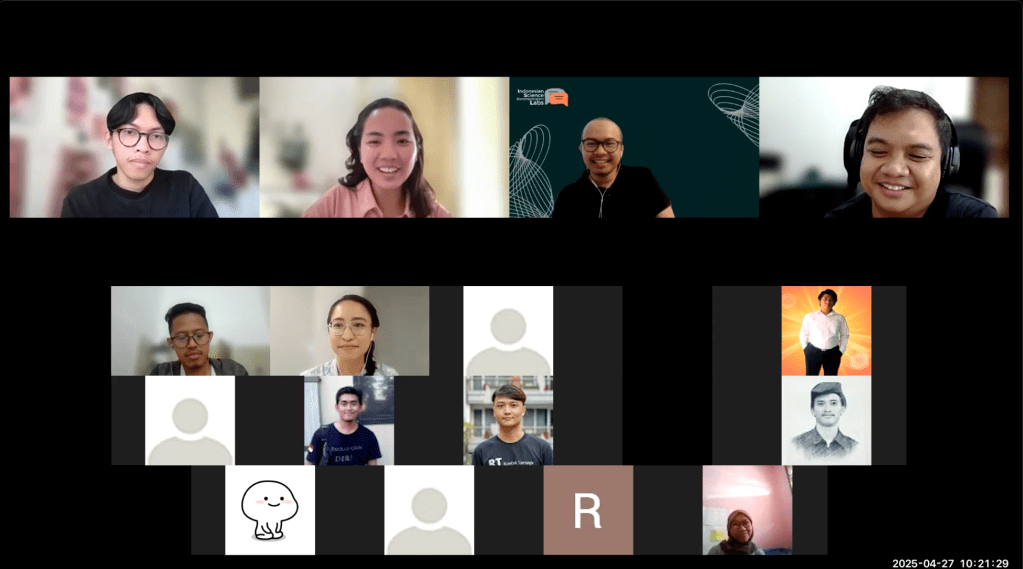
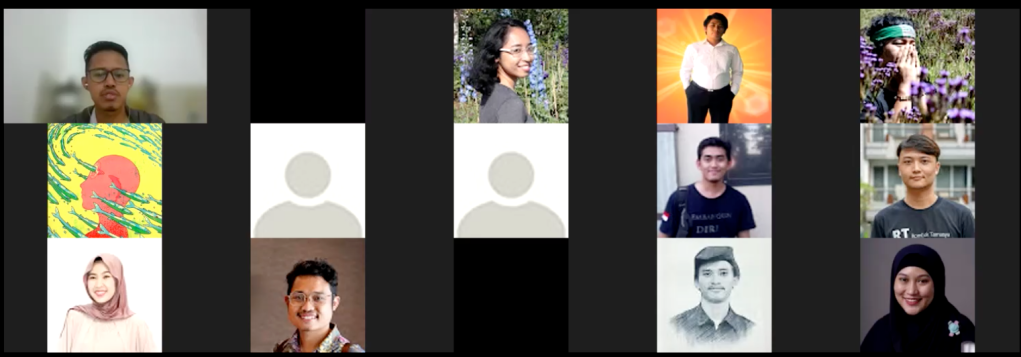
Jalan Menuju Pendidikan Formal Komunikasi Sains
Isma membayangkan akan sering pergi diving dan melihat ikan-ikan cantik ketika dirinya kuliah di Oseanografi Institut Teknologi Bandung (ITB). Ternyata dirinya malah banyak berkutat di laptop dan berkutat dengan rumus-rumus matematis dan kalkulus. Isma juga pernah magang di Oseanografi LIPI di daerah Ancol Jakarta Utara.
Dari kuliah dan magang itu Isma seperti menyadari dan yakin kalau dirinya sepertinya tidak akan menjadi Saintis yang ia imajikan seperti bekerja dari Lab ke Lab.
Kesadaran tersebut kian menguat ketika Isma melanjutkan studi di University College London (UCL). Ia menemukan bahwa komunikasi sains tidak hanya relevan di konferensi akademik atau dalam bentuk artikel jurnal, tetapi juga dalam konteks kehidupan masyarakat sehari-hari. Seperti yang sekarang ia jalani banyak berhubungan dengan masyarakat pesisir, menikmati hari-harinya sebagai videografer dan periset dalam pembuatan film.
Banyak yang dipelajari Isma ketika dirinya kuliah. Amatan Isma, komunikasi sains khususnya di Britania Raya dan Selandia Baru tidak berfokus pada kegiatan akademik saja. Jurusan komunikasi sains ini bekerjasama langsung dengan rumah produksi podcasting, life film making, dan documentary. Ekosistem keilmuan dalam pengembangan komunikasi sains dibentuk dengan pendekatan interdisiplin.
Berbeda dengan Isma, Galih mengawali ketertarikannya pada komunikasi sains bukan dari bangku kuliah, melainkan melalui komunitas informal “Eksakta” saat masih menjadi mahasiswa ilmu fisika di Universitas Brawijaya (UB) Malang. Bersama teman-temannya, ia mulai menyebarkan konten sains melalui aplikasi LINE dan kemudian terlibat dalam platform edukasi digital “Kok Bisa”. Baru setelah itu, ia melanjutkan pendidikan formal di program Science Education and Communication di Utrecht University, Belanda.
“Buat apa belajar fisika? Apa kaitannya dengan dunia nyata,” ujar Galih memulai cerita.
Memulai cerita sains memang bisa lewat apa saja. Ia dan beberapa kawannya mulai berkumpul lewat komunitas Eksakta dan memproduksi narasi tentang sains. Ketika itu mereka menyampaikannya lewat media sosial Line. Juga dirinya ketika bergabung dalam Kok Bisa yang memuat konten-konten seputar sains dan gaya hidup.
Ragam Media Komunikasi
Apakah belajar komunikasi sains harus memahami media atau medium komunikasinya? Pertanyaan ini muncul dari salah satu peserta diskusi.
Pertanyaan ini sangat penting karena apa yang diungkapkan Galih dan Isma, pada kenyataanya komunikasi sains kaya akan medium dan sebetulnya apa yang mereka pelajari?
Galih merasakan betul bagaimana dirinya belajar komunikasi sains secara formal dan informal ketika dirinya belajar di Science Education and Communication at Utrecht University, Belanda. Terutama ketika komunikasi sains yang formal dan informal itu harus berhadapan dengan publik dan pemegang kebijakan.
“Irisan dari dua bidang (formal dan informal) itu sih,” ujar Galih.
Di Utrecht, Galih mempelajari irisan antara komunikasi sains formal dan informal. Kurikulum yang ia ikuti menggabungkan teori komunikasi, pendidikan, teknologi pembelajaran, dan isu-isu kontemporer seperti pseudosains. Ia menekankan pentingnya riset dalam pengembangan praktik komunikasi sains, serta perlunya pendekatan project-based learning dalam membangun kompetensi.
Isma maupun Galih juga merasakan belajar filsafat menjadi salah satu bagian dari mata kuliah yang dipelajari dalam pendidikan komunikasi sains.
Isma membagi pengalamannya selama kuliah komunikasi sains, para mahasiswa sebetulnya dapat mengerjakan sesuatu yang menjadi bidang yang mereka sukai. Memang beberapa universitas memiliki ‘working placement’ untuk mengerjakan proyek berbasis komunikasi sains. Juga pelbagai medium yang dapat dieksplorasi oleh setiap mahasiswa.
Misalnya saja mahasiswa dapat mengerjakan proyek riset maupun karya berbasis proyek di rumah produksi film, berkontribusi menjadi penulis di majalah sains, membuat podcast dan medium lainnya.
Dan di dalam kuliah teori maupun yang berbasis praktikal akan didatangkan para praktisi di bidang komunikasi sains, mulai membicarakan bagaimana membuat proyek komunikasi sains yang sesuai dengan audiens yang akan dicapai.
Hal yang menarik dari Galih dan Isma adalah bagaimana komunikasi sains ini juga berkaitan dengan bagaimana para komunikator sains dapat mengkomunikasikan sains ke publik. Bagaimana bercerita sains lewat museum, percetakan, video dan film, serta memikirkan program pendidikan yang dapat diakses oleh publik.
Komunikator Sains, Bukan Sekadar Penerjemah
Dalam diskusi, muncul pula pertanyaan pematik dari Kuka, Jurnalis sains di Jakarta Post yang relevan hingga saat ini. Apa perbedaan antara jurnalis sains dan komunikator sains? Isu ini penting karena kedua peran tersebut sering kali tumpang tindih, namun memiliki orientasi institusional dan fungsi sosial yang berbeda.
Ilham menegaskan bahwa jurnalis sains lebih terikat pada logika pemberitaan dan media massa, sementara komunikator sains cenderung bergerak dalam kerangka pendidikan, advokasi, atau pengembangan kapasitas publik. Keduanya kerap dipersepsikan hanya sebagai “penerjemah sains”, padahal tantangan terbesar justru bagaimana menyampaikan kompleksitas proses ilmiah kepada publik tanpa kehilangan akurasi maupun relevansi sosialnya.
Langit Rinesti, salah satu peserta diskusi, menambahkan pentingnya kolaborasi antara saintis dan komunikator sains untuk memilih medium komunikasi yang paling efektif. Sementara itu, Isma mengingatkan adanya jarak epistemologis antara pemahaman sains oleh publik dan narasi ilmiah resmi. Di sinilah pentingnya konteks sosial dan kearifan lokal dalam mendesain strategi komunikasi yang inklusif.
Menuju Ekosistem Komunikasi Sains Indonesia
Perkembangan komunikasi sains di negara-negara Global Utara ditopang oleh ekosistem institusional yang kuat dengan jalan kolaborasi antar universitas, industri kreatif, dan lembaga publik. Namun, bagaimana dengan di negara-negara Global Selatan seperti Indonesia?
Tantangan utama adalah membangun ekosistem yang memungkinkan komunikasi sains berperan aktif dalam pembentukan kebijakan, edukasi publik, serta pencegahan disinformasi. Hal ini menjadi penting di tengah maraknya fenomena pseudosains dan kepercayaan tradisional yang kuat di masyarakat.
Maka, pembelajaran komunikasi sains di Indonesia perlu mengintegrasikan pendekatan lintas disiplin seperti komunikasi, pendidikan, kebijakan, dan budaya untuk menjawab tantangan epistemologis dan struktural di era pascakebenaran dan ketidakpastian ilmiah. Isu-isu global tentang keterbukaan sains atau demokratisasi sains juga menjadi bahan diskusi yang menarik ke depannya untuk didiskusikan dalam forum diskusi di IDSCL.
Tinggalkan komentar